Semua Orang Mengeluh Tentang Gen Z
Sebagai orang yang bekerja di lingkungan kampus, tentu saja kehidupan saya tidak bisa lepas dari Gen Z. Wajar karena seluruh mahasiswa sarjana dan sebagian mahasiswa pascasarjana termasuk dalam generasi yang sedang menjadi bintang pembicaraan di berbagai kesempatan.
Keluhan santer sering terdengar mengenai generasi yang terlahir antara tahun 1997 – 2012 ini. Mulai dari sulit diajak bekerja sama hingga perilaku yang tidak sesuai “norma”. Sepertinya Gen Z adalah generasi yang paling banyak dianalisis dari seluruh generasi yang pernah ada.
Dari interaksi sehari-hari, saya memang merasakan perbedaan yang mencolok dari “standar kehidupan” Gen Z dengan “standar kehidupan” yang saya miliki sebagai bagian dari Gen Y atau Millenial. Perbedaan tersebut tak jarang menjengkelkan, bahkan sampai membuat saya naik pitam. Tapi lebih seringnya kelakuan anak-anak Gen Z ini membuat saya heran.
Buat saya mereka bagaikan alien yang tidak dapat saya pahami. Pola pikir, keputusan yang diambil, dan tindak tanduknya sungguh membingungkan. Kadang sampai pada tahap yang menurut saya tidak masuk akal.
Tapi setelah saya pikir-pikir, jangan-jangan memang frekuensi otaknya sudah berbeda. Bagaimanapun antara Gen Y dan Gen Z lahir di milenium yang berbeda. Dunia juga berubah sedemikian pesat dari mereka lahir hingga dewasa. Jadi tidak heran kalau standar kehidupan mereka memang tak sama.
Perbedaan umur juga tidak bisa bohong. Gen Z yang masih berusia kurang dari 30 tahun (atau bahkan belasan) tentu berbeda pola pikir (dan energi) dengan millenial yang saat ini sudah ada di tahap lansia muda dewasa seutuhnya . Sudah banyak ditempa cobaan hidup sehingga lebih kaya pengalamannya, walaupun belum tentu lebih bijaksana.
Kesempatan Kerjasama Dengan Gen Z
Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan bekerja sama dengan mahasiswa, yang keseluruhannya adalah Gen Z, untuk menyelenggarakan beberapa acara. Dari beberapa kesempatan tersebut, saya belajar banyak mengenai generasi penguasa Indonesia dalam dua dekade ke depan ini.
Sebelum saya menjelaskan apa saja hal-hal yang saya pelajari, saya sampaikan dulu disclaimer terkait situasi yang saya alami. Hal ini penting saya sampaikan terlebih dahulu, karena mungkin saja, pengalaman saya bekerja dengan Gen Z menjadi tidak relevan untuk orang lain, karena demografi Gen Z nya berbeda.
- Hubungan kerjasama yang saya lakukan dengan mahasiswa Gen Z bukan sebagai atasan dan bawahan. Posisi saya sama dengan mereka, sebagai panitia penyelenggara acara. Cuma karena saya (jauh) lebih tua, biasanya saya yang harus memberikan keputusan kalau ada apa-apa. Peran saya lebih seperti pengarah.
- Dari keseluruhan acara yang diselenggarakan, jika gagal atau kacau pelaksanaannya tidak memiliki konsekuensi yang fatal. Paling malu saja atau diprotes oleh pemangku kepentingan karena acaranya berantakan.
- Saya menyadari sepenuhnya kalau yang bekerja sama dengan saya ini adalah mahasiswa, yang masih belajar. Jadi ekspektasi saya, mereka memang masih perlu diberi penjelasan, pemahaman, dan pengertian.
- Karena nasib dan reputasi saya tidak dipertaruhkan untuk menyelenggarakan acara-acara tersebut, jadi saya cukup santai mengerjakannya. Mungkin kalau ada hal yang lebih besar yang jadi taruhannya, saya juga akan ngegas di setiap belokan dan tikungan.
- Gen Z yang bekerja sama dengan saya berasal dari lingkungan yang homogen dari sisi tingkat pendidikan. Mereka adalah mahasiswa di dua program studi paling ternama, di salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di Indonesia. The elitest of the elites. Punya keistimewaan lebih dari sisi kecerdasan dan status, ditambah kebanyakan dari mereka adalah anak baik yang tidak neko-neko.
Setelah 3 Wisuda, 1 Reuni, dan 1 Minggu Keriaan
Dari hasil pengamatan saya setelah menyelenggarakan 5 acara bersama Gen Z semenjak tahun 2023, saya menyimpulkan bahwa yang membuat Gen Z ini membingungkan adalah sifat-sifat mereka yang kontradiktif. Sepertinya hal ini yang membuat generasi pendahulunya menjadi kesulitan untuk memahami, pola pikir dari anak-anak ini. Maunya apa to??
Berikut saya sampaikan beberapa kontradiksi sifat Gen Z yang saya amati. Perlu dicatat walaupun mungkin kesannya negatif, tapi saya tidak beranggapan sifat-sifat kontradiktif yang dimiliki oleh Gen Z sepenuhnya jelek. Melainkan saya justru menganggapnya sebagai suatu hal yang baru, yang perlu dipahami konteksnya, daripada terus menerus bingung dan naik darah sendiri menghadapinya.
Sangat Sosial Tapi Individualis

Media sosial adalah bagian hidup Gen Z. Sepertinya sangat jarang Gen Z yang tidak terpapar dengan sarana komunikasi online. Dengan kemudahan untuk terhubung dengan dunia luar, Gen Z dikenal sebagai generasi yang sangat sosial. Kebanyakan dari mereka memiliki jejaring sosial yang luas dan terpapar berbagai isu sosial dengan lebih cepat.
Dengan cepat mereka menyambut ide-ide kolaborasi juga dengan bersemangat mengikuti tren digital dan mendukung isu-isu sosial asalkan semuanya ada di dunia maya. Mereka sangat percaya bahwa media sosial adalah kunci dari segala komunikasi di dunia.
Masalahnya dibalik komunikasi yang sangat terbuka di dunia maya, saya perhatikan generasi ini lebih individualis daripada pendahulunya. Tidak tau cara menghubungi teman dengan cepat karena hanya bisa menghubungi lewat DM Instagram adalah salah satu hal yang membuat saya tercengang. “Kamu tidak punya nomor teleponnya?”, adalah pertanyaan yang berkali kali saya ajukan dengan keheranan dan selalu dijawab dengan singkat “Tidak”.
Begitupun dengan omelan panjang lebar saya karena harus mengulang-ngulang informasi yang sama karena tidak ada yang berminat mengkomunikasikan informasi yang diterima kepada teman yang membutuhkan informasi yang sama.
Saat penyelenggaraan acara sifat Gen Z yang sangat mengandalkan sosial media terlihat jelas di bagian publikasi dan penggalangan dana. Buat mereka posting di sosial media sudah cukup sebagai corong informasi. Pendekatan personal seperti mendatangi langsung orang yang ingin diberikan informasi tidak terpikirkan oleh mereka.
Akibatnya mereka seringkali menghadapi kesulitan ketika informasi tersebut tidak sampai pada orang-orang yang menjadi target informasi tersebut. Seperti pendaftar peserta seminar dan lomba yang hanya sedikit jumlahnya karena jangkauan informasinya hanya sampai ke segelintir orang saja.
Pintar Menampilkan Diri di Dunia Maya Tapi Kesulitan Berinteraksi di Dunia Nyata

Masih terkait dengan komunikasi, sebagai generasi yang tumbuh besar dengan internet, Gen Z memang lebih nyaman berkomunikasi melalui media sosial, forum online, dan aplikasi pesan instan. Dengan mudah, mereka membangun persona, mengekspresikan opini, dan menjalin relasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia.
Namun, ada ironi yang muncul: meskipun mereka terlihat begitu komunikatif di dunia maya, banyak dari mereka justru mengalami kesulitan saat berinteraksi secara langsung di dunia nyata.
Fenomena ini bukan tanpa sebab. Sejak kecil, Gen Z terbiasa dengan komunikasi berbasis teks dan visual, di mana mereka bisa menyusun kata-kata dengan hati-hati sebelum mengirim pesan. Di dunia nyata, interaksi terjadi secara spontan, tanpa fitur “edit” atau “delete.” Hal ini membuat Gen Z kurang memiliki kemampuan sosial untuk menangani situasi yang membutuhkan kontak mata, membaca ekspresi wajah, atau percakapan yang tidak gamblang.
Ini alasan mengapa Gen Z sering dianggap tidak sopan. Sepertinya bukan tidak sopan sih, melainkan kurang bisa menempatkan diri. Karena memahami social clue tidak otomatis terinstal di diri mereka. Akibatnya seringkali interaksi langsung mereka dengan orang lain menjadi canggung bahkan tak jarang menyinggung. Karena sedikit yang bisa mengerti bahwa orang lain bukan mesin yang bisa paham apa yang mereka mau dan menuruti keinginan mereka.
Pada pengalaman saya menyelenggarakan acara, masalah muncul ketika para Gen Z yang menjadi panitia tidak paham cara memperlakukan atau menghadapi pemangku kepentingan. Kemampuan komunikasi memang menjadi peer tersendiri untuk Gen Z. Email, linkedin, atau bahkan DM Instagram adalah media yang dianggap lebih dapat diterima daripada pendekatan personal.
Kontak langsung melalui aplikasi pesan instan seperti Whatsapp sangat mereka hindari. Padahal orang-orang yang perlu mereka hubungi kebanyakan berasal dari generasi sebelumnya yang tidak terlalu terlibat dengan sosial media.
Akibatnya banyak kesalahpahaman yang terjadi. Seperti pengisi acara yang tidak diberikan brief dan rundown dengan jelas atau sponsor yang tidak menurunkan dana padahal logo sudah tercetak di publikasi (dari awal sponsor tersebut tidak pernah secara definitif mengiyakan akan menjadi sponsor).
Ingin Autentik Tapi Homogen

Saya pikir menjadi diri sendiri adalah salah satu tujuan hidup Gen Z. Dengan meningkatnya kesadaran mengenai mental health, dengan segenap hati pemuda pemudi ini mencari identitas yang benar-benar mencerminkan diri mereka. Terkadang sampai menolak standar yang dirasa dipaksakan demi originalitas. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, gen Z adalah yang paling berusaha untuk mengenali diri sendiri.
Masalahnya kebanyakan Gen Z mencari jati dirinya menggunakan perbandingan atau referensi yang dapat dilihat di sosial media. Sehingga dalam usaha-usaha untuk menjadi diri sendiri mereka malah mengopi jati diri orang lain. Menjadikan Gen Z ini menjadi generasi yang lebih homogen daripada generasi sebelumnya.
Ada daftar mengenai hal-hal yang dianggap “autentik.” Ada penampilan yang dianggap mencerminkan diri sendiri, tapi ternyata mengikuti tren yang sama. Ada opini yang disebut “berani dan jujur” tetapi justru bergaung dalam ruang gema yang seragam. Bahkan, dalam gerakan menolak standar-standar mainstream, muncul standar-standar lain yang segera berubah menjadi mainstream dengan banyaknya pengikut.
Fenomena ini mencerminkan paradoks besar: Gen Z ingin menjadi unik, tetapi tidak ingin terasing. Mereka ingin menonjol, tetapi tetap dalam batas yang dapat diterima oleh kelompok mereka. Keautentikan yang mereka kejar tidak sepenuhnya individual, melainkan kolektif. Akibatnya, kebebasan berekspresi sering kali berbenturan dengan tekanan sosial tak kasat mata yang menentukan apa yang “benar” dan apa yang “tidak dapat diterima.”
Pada akhirnya, kontradiksi ini menunjukkan bahwa keautentikan bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan sesuatu yang selalu dinegosiasikan dalam konteks sosial. Gen Z ingin bebas, tetapi tetap ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu. Mereka ingin berbeda, tapi tetap sama.
Sebetulnya saya kagum pada kreativitas anak-anak Gen Z. Jika diarahkan dengan benar mereka bisa bekerja melebihi ekspektasi yang diberikan. Tapi kreativitas tersebut memang harus dipantik dan disemangati. Karena menjadi pelopor atau pencetus ide tanpa referensi kesuksesan bukanlah hal yang diminati.
Idealis Tapi Pragmatis
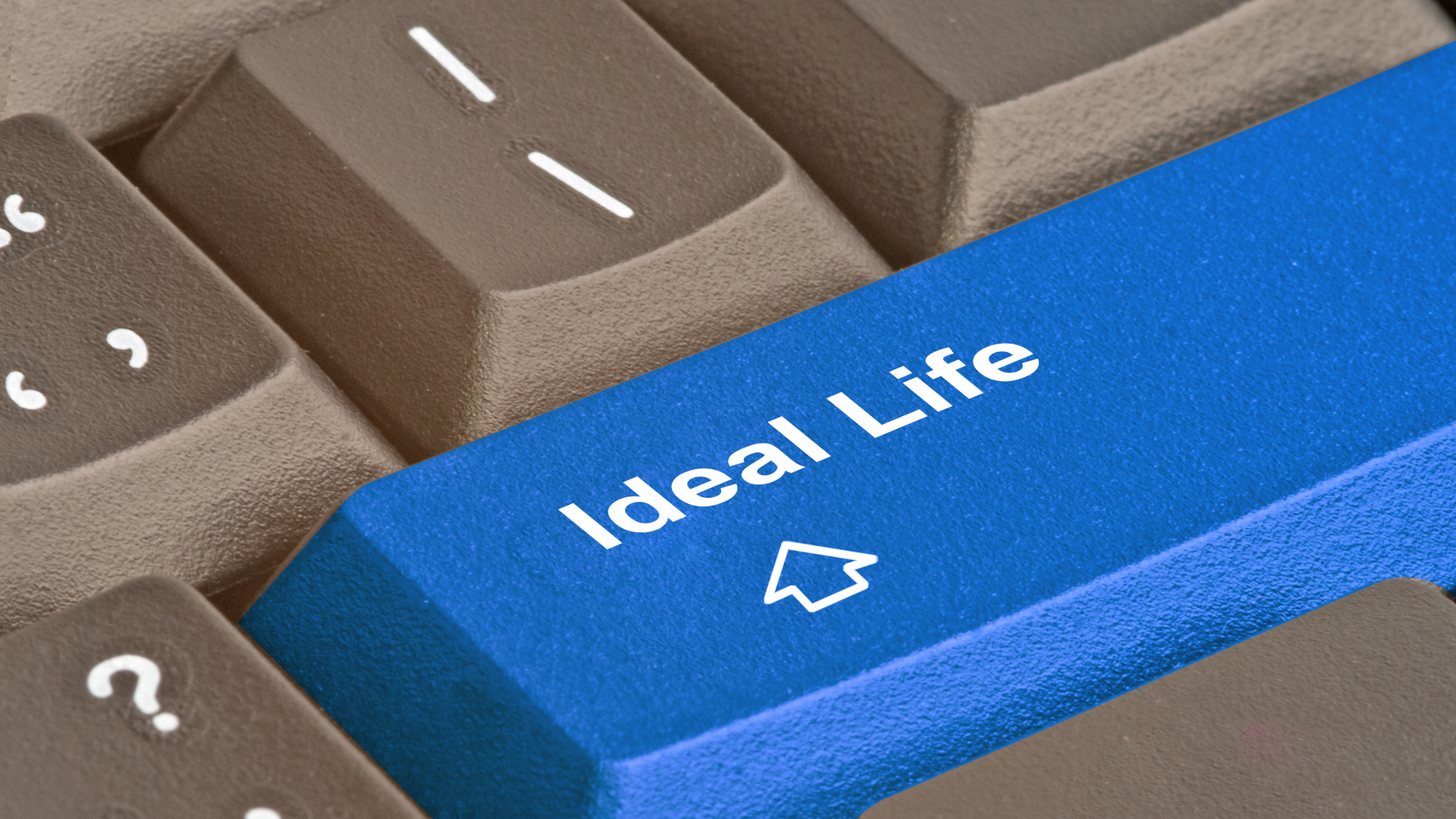
Dibandingkan dengan generasi lainnya, menurut saya Gen Z adalah yang paling idealis. Mereka sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai alur kehidupan. Kesuksesan adalah sesuatu yang sudah dapat mereka definisikan dengan baik. Tidak seperti millenial yang kebanyakan masih mengikuti kemana angin membawa diri, dengan tujuan yang sudah jelas, Gen Z nampak lebih semangat untuk membuat takdir sendiri.
Masalahnya, karena melihat contoh hanya dari beberapa platform yang cenderung homogen, tujuan hidup yang mereka anggap ideal cenderung hanya terbatas di beberapa pilihan saja. Akibatnya banyak yang terjebak pada fix mindset. Tujuannya terbatas dan cara menggapainya juga lurus saja.
Contohnya: hidup bahagia adalah punya uang banyak. Agar bisa punya uang banyak maka harus berusaha bekerja di perusahaan ternama bergaji besar. Untuk bekerja di perusahaan besar harus punya transkrip dan curriculum vitae (CV) yang mumpuni. Sehingga kuliah adalah untuk mengejar nilai dan membangun CV yang disukai perusahaan.
Tanpa memberikan ruang untuk alternatif lainnya, akhirnya langkah-langkah yang diambil cenderung pragmatis. Fokus pada hal-hal yang tangible seperti indeks nilai dan melupakan yang intangible seperti networking di dunia nyata. Maka dari itu tingkat stres Gen Z lebih tinggi, karena terpeleset sedikit mereka langsung merasa gagal. Tidak bisa memenuhi “standar” hidup yang mereka tetapkan sendiri.
Itulah menurut saya, mengapa berinteraksi dengan Gen Z seringkali terasa sangat transaksional. Gen Z harus tau dengan pasti apa yang bisa mereka dapatkan sebagai imbalan untuk semua hal yang mereka lakukan. Terutama untuk hal-hal yang tidak ada dalam roadmap grand design “tujuan hidup” mereka atau belum terbukti ada “keuntungannya”. Jika imbalannya dianggap tidak sesuai, maka buat mereka tidak ada pentingnya untuk dikerjakan. Untuk apa? buang-buang waktu saja.
Jika inisiatifnya bukan dari mereka sendiri, mengajak mahasiswa untuk mengadakan suatu acara adalah sebuah hal yang sulit. Pada saat mereka berinisiatif untuk membuat acara, melihat susunan panitianya membuat saya tak habis pikir. Jumlahnya bisa satu RT dan semua orang harus punya jabatan. Karena jabatan diperlukan untuk dicantumkan ke dalam CV. Itupun mereka masih kesulitan mencari orang ketika ada kondisi darurat.
Saya jadi pusing memikirkan negara ini dalam 20 tahun kedepan. Dipimpin baby boomers saja menterinya ada 46, gimana saat Gen Z jadi presiden? mungkin kabinetnya bisa 1 kelurahan sendiri.
Independen Tapi Butuh Validasi

Gen Z dikenal sebagai generasi yang independen. Mereka percaya diri mampu dan memiliki keinginan kuat untuk menavigasi hidup dengan cara mereka sendiri. Hanya saja yang mengherankan Gen Z selalu perlu validasi. Seperti takut melangkah dan mengambil keputusan. Setiap sampai di persimpangan kebanyakan dari mereka harus bertanya dulu ke orang lain, jalan mana yang harus diambil. Sebelum ada jawabannya, mereka akan diam mematung.
Mungkin ini adalah dampak dari interaksi yang intens di media sosial. Setiap saat mereka merasa ada ribuan mata yang memandangi mereka. Baik di momen yang membanggakan atau memalukan. Sebetulnya komentar orang tentu saja ada di setiap masa. Akan tetapi jika millenial merespon dengan defensif, maka respon Gen Z adalah tidak melangkah sebelum tahu pasti apa yang akan terjadi.
Masalahnya di dunia ini ada banyak hal-hal random yang tidak akan diketahui ujung pangkalnya jika tidak dicoba sendiri. Karena tidak semua hal bisa dicari hubungan sebab akibatnya di internet. Jadi terkadang orang perlu dengan percaya diri mengambil risiko untuk mengambil salah satu jalan. Daripada menunggu dan menyebabkan kemacetan.
Perasaan takut salah dan takut dianggap konyol saya rasa menjadi phobia yang jamak terjadi dikalangan Gen Z. Saya perhatikan di berbagai acara mereka segan untuk menyampaikan pendapat atau melontarkan pertanyaan di muka umum. Itulah mengapa kritik dan saran adalah hal yang tidak bisa mereka terima dengan mudah.
Multitasking Tapi Tidak Bisa Fokus

Generasi Z dikenal sebagai generasi digital native yang tumbuh dengan teknologi di ujung jari mereka. Mereka bisa melakukan banyak hal sekaligus—mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas, menonton video sambil membalas chat, atau scrolling media sosial di tengah-tengah rapat daring. Multitasking seolah menjadi keahlian alami mereka.
Namun, di balik kemampuan multitasking yang mengesankan, ada ironi yang mencolok: Gen Z tidak mampu mempertahankan fokus dalam waktu yang lama. Dengan informasi yang terus mengalir tanpa henti, konsentrasi sering kali terpecah, membuat mereka mudah terdistraksi. Perhatian mereka berpindah-pindah dari satu notifikasi ke notifikasi lainnya, dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, seperti selancar di lautan digital tanpa tujuan yang jelas.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah benar Gen Z mampu multitasking, atau justru terjebak dalam pola kerja yang sekadar berpindah dari satu distraksi ke distraksi lain? Dalam dunia yang menuntut kecepatan, mereka tampak sibuk sepanjang waktu, tetapi sering kali merasa kelelahan tanpa hasil yang benar-benar maksimal.
Berdasarkan pengalaman, membuat checklist tugas menjadi jalan ninja saya untuk bekerja sama dengan Gen Z. “Bagaimanapun caranya, saya cuma mau semua yang ada di check list tersebut lengkap”, itu saja perintah saya. Hal tersebut ternyata cukup membantu mereka untuk fokus. Bahkan ide-ide kreatif bisa bermunculan tanpa menyimpang terlalu jauh dari tujuan.
Membagi tugas dengan checklist juga dirasa lebih nyaman untuk mereka, karena bisa bekerja sama satu sama lain dengan tetap menjaga ruang pribadi. Tanpa disadari mereka bekerja untuk melaksanakan tujuan yang sama dan bukan hanya terpaku pada job desc yang melekat pada title yang mereka sandang. Dengan checklist juga lebih mudah bagi pengawas untuk dapat memeriksa semua pekerjaan.
Untuk selalu harus memikirkan terlebih dahulu alasan dari semua perintah, tentu jauh lebih melelahkan daripada cuma melontarkan perintah saja. Maka dari itu, rasanya uban saya bertambah drastis beberapa tahun ini. Tapi karena sepertinya saya akan tetap bekerja sama dengan generasi ini sampai beberapa tahun ke depan, sepertinya saya harus mulai menerima saja, kalau harus menjelaskan segala macam hal dan berusaha lebih untuk mengkondisikan situasi, hanya supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan tujuannya.
Penutup
Gen Z memang unik. Dibalik segala omelan saya, tak jarang saya tertawa melihat tingkah mereka. Dari interaksi dengan mereka juga saya belajar banyak mengenai apalagi kalau bukan parenting. Ya, sedikit banyak saya menyadari kalau sifat-sifat Gen Z yang seperti itu adalah buah dari perilaku generasi orang tuanya. Generasi saya dan yang lebih tua. Maka dari itu setiap kali menghadapi Gen Z yang memusingkan, sedikit banyak saya judging orang tuanya. Haha.
Tulisan ini dibuat berdasarkan pengamatan pada sekelompok orang saja. Tentu saja tidak bijaksana jika digeneralisir untuk 2 milyar manusia yang termasuk dalam Gen Z. Tapi mungkin hasil pengamatan saya bisa dijadikan masukan untuk lebih memahami generasi ini, jika ada yang merasa memerlukannya. Paling tidak kalau mau menggosip jadi ada dasarnya kan ya?
Apakah ada yang punya pendapat berbeda tentang Gen Z? Yuk tulis di komentar ya Mah!






Seru ya teh Restu.
I feel you … Mahasiswaku tahun ini ya rerata kelahiran 2002-2005.
Anakku kedua lahir 2000 dan si bungsu 2007.
Salah satu yang bisa bikin gen-Z lebih dimengerti adalah cara kita orang tuanya memperlakukan mereka. Mereka juga bingung dengan kelakuan gen-Y atau sebelumnya hehehe…
Satoe koencie adalah komunikasi yang lebih terbuka.
We’re in the same boat, kak/ibu Dewi Laily Purnamasari. 😁
Met malam kak Restu. Sebagai seorang pengajar di sebuah universitas di Yogyakarta, saya juga banyak melihat perilaku banyak mahasiswa (tidak semuanya :-D) gen-Z yang dahi mengernyit. Banyak perilaku atau etika sederhana dan mendasar yang mereka tidak mengerti, tidak lakukan di lingkungan kampus, seperti masuk kelas tanpa mengetuk, meninggalkan kelas (mungkin mau ke toilet), tanpa ada sepatah kata yang diucapkan …